Cardiac heart Failure (CHF)
A. STEP 7 : PEMBAHASAN LO
1. Defenisi Gagal
Jantung
Gagal jantung adalah suatu keadaan ketika jantung
tidak mampu mempertahankan sirkulasi yang cukup bagi kebutuhan tubuh, meskipun
tekanan pengisian vena normal (Muttaqin, 2009).
Gagal jantung adalah
ketidakmampuan jantung untuk untuk
memompa darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan akan oksigen dan
nutrisi (Brunner &
Suddarth, 2010).
Gagal jantung adalah suatu
sindrom kompleks yang terjadi akibat gangguan jantung yang merusak kemampuan ventrikel
untuk mengisi dan memompa darah secara efektif
(LeMone, M.Burke, &
Bauldoff, 2015).
2. Klasifikasi Gagal
Jantung
Tingkat
keparahan gagal jantung sering diklasifikasikan berdasarkan gejala pasien .
Klasifikasi New York Heart Association (NYHA) dijelaskan pada Tabel 1 dan American College of
Cardiology dan American Heart Association
(ACC dan AHA
) telah mengembangkan sistem klasifikasi gagal jantung dijelaskan pada Tabel 2.
) telah mengembangkan sistem klasifikasi gagal jantung dijelaskan pada Tabel 2.
Tabel 1
Klasifikasi gagal jantung menurut NYHA
|
NEW YORK HEART ASSOCIATION (NYHA)
CLASSIFICATION OF HEART FAILURE
|
||
|
Klasifikasi
|
Tanda dan Gejala
|
Prognosis
|
|
Kelas I
|
Tidak terdapat batasan
dalam melakukan aktifitas fisik. Aktifitas fisik sehari-hari tidak
menimbulkan kelelahan, palpitasi atau sesak nafas
|
Baik
|
|
Kelas II
|
Terdapat batasan aktifitas
ringan. Tidak terdapat keluhan saat istirahat,
|
Baik
|
|
Kelas III
|
Terdapat Batasan aktifitas
bermakna. Tidak terdapat keluhan saat istirahat, tetapi aktifitas fisik
ringan menyebabkan kelelahan, palpitasi dan kelelahan
|
Sedang
|
|
Kelas IV
|
Tidak dapat melakukan
aktifitas fisik tanpa keluhan. Terdapat gejala saat istirahat. Keluhan meningkat
saat melakukan aktifitas
|
Berat
|
|
Klasifikasi
|
Kriteria
|
|
Stadium A
|
Memiliki risiko tinggi
untuk berkembang menjadi gagal jantung. Tidak terdapat gangguan struktural
atau fungsional jantung, tidak terdapat tanda atau gejala.
|
|
Stadium B
|
Telah terbentuk penyakit
struktur jantung yang berhubungan dengan perkembangan gagal jantung, tidak
terdapat tanda gejala
|
|
Stadium C
|
Gagal jantung yang
simtomatik berhubungan dengan penyakit struktural jantung yang mendasari
|
|
Stadium D
|
Penyakit jantung
struktural lanjut serta gejala gagal jantung yang sangat bermakna saat
istirahat walaupun sudah mendapat terapi medis maksimal (refrakter)
|
Sumber: (Brunner & Suddarth, 2010)
3. Etiologi Gagal
Jantung
1) Disfungsi
miokard paling sering disebabkan oleh penyakit arteri koroner, kardiomiopati,
hipertensi, atau kelainan katup. Pasien dengan diabetes melitus juga berisiko
tinggi untuk gagal jantung
(Brunner &
Suddarth, 2010).
a) Aterosklerosis
koroner adalah penyebab utama gagal
jantung, dan penyakit arteri koroner ditemukan pada lebih dari 60% pasien
dengan gagal jantung.
b) Kardiomiopati
adalah penyakit miokardium. Ada tiga jenis: dilatasi, hipertrofi, dan
restriktif. Kardiomiopati
dilatasi, jenis kardiomiopati yang paling umum, menyebabkan nekrosis dan
fibrosis seluler yang difus, yang menyebabkan penurunan kontraktilitas
(kegagalan sistolik). Kardiomiopati dilatasi dapat bersifat idiopatik (penyebab
tidak diketahui) atau dapat terjadi akibat proses peradangan, seperti
miokarditis, atau dari agen sitotoksik, seperti alkohol atau doxorubicin
(Adriamycin). Kardiomiopati hipertrofik dan kardiomiopati restriktif
menyebabkan penurunan distensibilitas dan pengisian ventrikel (kegagalan
diastolik). Biasanya, gagal jantung akibat kardiomiopati menjadi kronis dan
progresif. Namun, kardiomiopati dan gagal jantung bisa sembuh setelah
penghilangan agen penyebab, seperti penghentian konsumsi alkohol.
c) Hipertensi sistemik atau pulmonal meningkatkan
afterload (resistensi terhadap ejeksi), yang meningkatkan beban kerja jantung
dan menyebabkan hipertrofi serat otot miokard. Ini dapat dianggap sebagai
mekanisme kompensasi karena meningkatkan kontraktilitas. Namun, hipertrofi
dapat mengganggu kemampuan jantung untuk mengisi dengan baik selama diastole,
dan ventrikel yang mengalami hipertrofi akhirnya dapat melebar dan gagal.
d) Penyakit jantung valvular juga merupakan penyebab gagal
jantung. Katup memastikan bahwa darah mengalir dalam satu arah. Dengan
disfungsi katup, darah semakin sulit bergerak maju, meningkatkan tekanan di
dalam jantung dan meningkatkan beban kerja jantung, yang mengarah ke gagal
jantung.
2)
Faktor sistemik
kondisi sistemik,
termasuk gagal ginjal progresif dan hipertensi yang tidak terkontrol,
berkontribusi terhadap perkembangan dan keparahan gagal jantung. Penyakit akut
seperti pneumonia dengan demam dan hipoksia meningkatkan laju metabolisme dan
dapat memicu gagal jantung. Semua kondisi ini membutuhkan peningkatan CO untuk
memenuhi kebutuhan oksigen sistemik, dan mereka menekankan miokardium yang
dikompromikan. Disritmia jantung dapat menyebabkan gagal jantung atau mungkin
akibat gagal jantung; Bagaimanapun, stimulasi listrik yang diubah merusak kontraksi
miokard dan mengurangi efisiensi keseluruhan fungsi miokard. Faktor-faktor
lain, seperti asidosis (pernapasan atau metabolisme), kelainan elektrolit, dan
obat antiaritmia, dapat memperburuk fungsi miokard.
4. Manifestasi klinis Gagal Jantung
Manifestasi
gagal jantung sebelah kiri terjadi akibat kongesti paru dan penurunan curah
jantung. Keletihan dan intoleransi aktivitas adalah manifestasi awal biasa
terjadi. Pusing dan sinkop juga dapat terjadi akibat penurunan curah jantung.
Kongesti paru menyebabkan dispnea, sesak napas pendek dan batu. Pasien dapat
mengalami ortopnea (sulit bernapas saat berbaring terlentang), yang membutuhkan
pemakaian dua atau tiga bantal atau sandaran bila tidur. Sianosis akibat
pertukaran gas dapat terlihat. Pada auskultasi paru, ronki inspirasi dan mengi
dapat terdengar pada dasar paru. Galop S3 juga dapat muncul, mencerminkan upaya jantung untuk mengisi ventrikel
yang sudah distensi.
Pada
gagal jantung sebelah kanan, peningkatan tekanan pada vaskular paru atau kerusakan
otot ventrikel kanan merusak kemampuan ventrikel kanan untuk memompa darah
menuju sirkulasi pulmonaris. Ventrikel dan atrium kanan menjadi distensi dan
darah terakumulasi dalam sistem vena sistemik. Peningkatan tekanan vena
menyebabkan organ abdomen menjadi kongesti dan adema jaringan perifer terjadi.
Jaringan yang terganggu cenderung terkena efek gravitasi. Edema terjadi pada
kaki dan tungkai atau jika pasien tirah baring, pada sakrum. Kongesti pada
pembuluh darah saluran pencernaan menyebakan anoreksia dan mual. Vena leher
distensi dan menjadi semakin terlihat bahkan saat pasien tegak akibat
peningkatan tekanan vena
Penurunan curah jantung mengaktifkan
penigkatan retensi garam dan air. Sehingga menyebabkan kenaikan berat badan dan
menigkatkan tekanan lebih lanjut dalam kapiler yang menyebabkan edema.
Nokturia, berkemih lebih dari satu kali pada malam hari, terjadi saat
cairan edema dari jaringan yang terganggu direabsorbsi saat pasien telentang .
Dispnea nokturna paroksismal (paroxysmal nocturnal dyspnea, PND), suatu
kondisi menakutkan yakni pasien terbangun pada malam hari karena maengalami
napas pendek akut, juga dapat terjadi. Dispnea nokturna paroksismal terjadi
saat caira edema yang terakumulasi selama siang hari direabsorbsi ke dalam
sirkulasi pada malam hari, menyebabkan kelebihan beban cairan dan kongesti
paru. Gagal jantung berat dapat menyebabkan dispnea pada saat istirahat serta
pada aktivitas yang menandakan cadangan jantung sedikit atau tidak ada. Galop
S3 dan S4 dapat terdengar pada saat auskultasi (LeMone et al., 2015).
5. Patofisiologi Gagal
Jantung
Sumber: (Brunner & Suddarth, 2010)
Pathway Gagal jantung
6. Komplikasi
Gagal Jantung
Mekanisme kompensasi yang dimulai pada gagal
jantung dapat menyebabkan komplikasi pada sistem tubuh lain. Hepatomegali
kongestif dan splenomegali kongestif yang disebabkan oleh pembengkakan sistem
vena porta menimbulkan peningkatan tekanan abdomen, asites dan masalah
pencernaan. Pada gagal jantung sebelah kanan yang lama, fungsi hati dapat
terganggu. Distensi miokardium dapat memicu disritmia, mengganggu curah jantung
lebih jantung. Efusi pleura dan masalah paru lain dapat terjadi. Komplikasi
mayor gagal jantung berat adalah syok kardiogenik dan edema paru akut (LeMone et al., 2015).
7. Pemeriksaan Diagnostik Gagal
Jantung
Diagnosis gagal jantung didasarkan pada riwayat, pemeriksaan fisik dan
temuan diagnostik (LeMone et al., 2015)
1.
Faktor natriuretik (ANF), juga disebut hormone natriuretic atrium (atrial
natriuretic hormone, ANH), dan peptide natriuretic tipe-B (B-type
natriuretic peptide, BNP) adalah hormon yang dilepaskan dari otot jantung
sebagai respon terhadap perubahan volume darah. Kadar hormon ini dalam darah
meningkatkan gagal jantung, meskipun begitu penting untuk mengingat bahwa kadar
BNP dapat naik pada wanita dan pada orang berusia diatas 60 tahun yang tidak
menderita gagal jantung. Dengan demikian kenaikan BNP tidak dapat digunakan
tunggal untuk mendiagnosis gagal jantung.
2.
Elektrolit serum diukur untuk mengevaluasi status cairan dan elektrolit.
Osmolalitas serum dapat rendah akibat retensi cairan. Kadar natrium, kalium,
dan klorida menyediakan dasar untuk mengevaluasi efek terapi, kalsium dan
magnesium juga diukur.
3.
Urinalisis, nitrogen urea darah (BUN), dan kreatinin serum diambil untuk
mengevaluasi fungsi ginjal.
4.
Pemeriksaan fungsi hati termasuk ALT, AST, dan LDH, bilirubin serum dan
kadar protein total dan albumin, dilakukan untuk mengevaluasi efek gagal
jantung yang mungkin pada fungsi hati.
5.
Pemeriksaan fungsi tiroid, termasuk kadar TSH dan LH, dilakukan karena
baik hipertiroidisme maupun hipotiroidisme dapat menjadi penyebab utama atau
penyerta gagal jantung.
6.
Pada gagal jantung akut, gas darah arteri (ABG) diambil untuk
mengevaluasi pertukaran gas pada jaringan dan paru.
7.
Sinar X dada dapat menunjukkan bendungan vascular paru dan kardiomegali
pada gagal jantung.
8.
Elektrokardiografi digunakan untuk mengidentifikasi perubahan EKG yang terkait
dengan pembesaran ventrikel dan mendetiksis aritmia, iskemia miokardium, infark.
9.
Ekokardiografi dengan studi aliran Doppler dilakukan untuk mengevaluasi
fungsi ventrikel kiri.
10.
Pencitraan radionuklida digunakan untuk mengevaluasi fraksi dan ukuran ventrikel.
8. Penatalaksanaan
Gagal Jantung
Tabel 3 Penatalaksanaan gagal jantung berdasarkan
stadium
|
Klasifikasi
|
Kriteria
|
Upaya
Penanganan Yang Dianjurkan
|
|
Stadium A
|
Memiliki
risiko tinggi untuk berkembang menjadi gagal jantung. Tidak terdapat gangguan
struktural atau fungsional jantung, tidak terdapat tanda atau gejala.
|
Tangani faktor
risiko dasar (mis.hipertensi) termasuk gangguan lemak
Inhibitor ACE
atau terapi penyekat reseptor-beta
( angiotensin -receptor blocker, ARB)
Latihan fisik
Pembatasan garam
Berhenti
merokok
Hentikan
alkohol, pemakaian obat terlarang
Kontrol
glukosa darah pada pasien sindroma metabolik
|
|
Stadium B
|
Telah
terbentuk penyakit struktur jantung yang berhubungan dengan perkembangan
gagal jantung, tidak terdapat tanda gejala
|
Sama seperti
stadium A
Inhibitor ACE
atau terapi ARB sesuai kebutuhan
Terapi
penyekat beta jika diindikasikan
|
|
Stadium C
|
Gagal jantung
yang simtomatik berhubungan dengan penyakit struktural jantung yang mendasari
|
Sama seperti
stadium A dan B
Terapi obat dengan
diuretic, inhibitor ACE, dan atau penyekat beta
Obat-obatan
tambahan sesuai indikasi, seperti antagonis aldosterone, ARB, digitalis,
hidralazin, nitrat
Pemacuan
Ventrikel atau defibrillator yang dapat ditanam (ICD) sesuai indikasi
|
|
Stadium D
|
Penyakit
jantung struktural lanjut serta gejala gagal jantung yang sangat bermakna
saat istirahat walaupun sudah mendapat terapi medis maksimal (refrakter)
|
Sama seperti
stadium A,B, dan C sesuai kebutuhan
Asuhan hospice
Monitoring
hemodinamik
Infus kontinu
agen inotropik positif
Penggantian
katup, transplantasi jantung sesuai indikasi
Bantuan
mekanik permanen, pembedahan eksperimental atau obat.
|
Sumber: (LeMone et al., 2015)
Tujuan penatalaksanaan pasien gagal jantung adalah untuk mengurangi
beban kerja jantung , meningkatkan kekuatan dan efisiensi kontraksi jantung
dengan bahan farmakologis dan menghilangkan penimbunan cairan tubuh berlebihan
dengan terapi diuretik , diet dan istirahat.
1.
Pemberian
medikasi (LeMone et al., 2015)
a) Inhibitor
Angiotensin–Converting Enzyme (ACE):
Enalapril
(vasotec), Captopril
(Capoten), Moexipril
(univasc), Quinapril
(Accupril), Trandolapril
(Mavik), Lisinopril (Prinivil,
Zestril), Fosinopril (Monopril), Perindropil (Aceon), Ramipril (Altace)
Indikasi
pemberian ACEI:
Fraksi
ejeksi ventrikel kiri ≤40% dengan atau tanpa gejala
Kontraindikasi
pemberian ACEI:
1)
Riwayat
angioedema
2)
Stenosis renal
bilateral
3)
Kadar kalium
serum > 5,0 mg/dL
4)
Serum kreatinin
> 2,5 mg/dL
b) Penyekat
beta angiotensin
II (ARB): Candesartan (Atacand), Losartan (Cozaar), Telmisartan (Micardis), Irbesartan (Avapro), Nesiritida (Natrecor), Vaisartan ( Diovan)
Indikasi
pemberian penyekat beta angiotensin:
1) Fraksi ejeksi ventrikel kiri ≤ 40%
2) Gejala ringan sampai berat (kelas fungsional II-IV
NYHA)
3) ACEI/ARB (dan antagonis aldosterone jika indikasi)
sudah diberikan
4) Pasien stabil secara klinis (tidak ada perubahan dosis
diuretic, tidak ada kebutuhan inotropic i.v dan tidak ada tanda retensi cairan
berat)
Kontraindikasi pemberian penyekat beta:
1)
Asma
2)
Blok AV
(atrioventrikular) derajat 2 dan 3, sindroma sinus sakit (tanpa pacu jantung
permanen), sinus bradikardia (nadi <50 menit="" span="" x="">
Inhibitor
ACE dan ARB mencegah serangan koroner akut dan mengurangi kematian akibat gagal
jantun. Inhibitor ACE mengganggu produksi angiotensin II, menyebabkan
vasodilatasi, penurunan volume darah, dan mencegah efeknya pada pembuluh darah.
Pada gagal jantung, inhibitor ACE mengurangi afterload dan memperbaiki curah
jantung dan aliran darah ginjal. Selain itu juga mengurangi kongesti paru, dan
edema perifer. Inhibitor ACE menekan pertumbuhan miosit dan menurunkan
remodeling ventrikel pada gagal jantung. Sementara efek farmakologik ARB adalah
serupa, obat ini menghambat kerja angiotensin II pada reseptor bukan mengganggu
produksinya.
c) Diuretik: Klorotiazid (Diuril), Furosemid (Lasix), Asam etakrinat
(Edecrin), Bumatedin
(Bumex), Toresemid (Demedex), Hidroklorotiazid (HydroDiuril), Spironolakton (Aldactone), Triamteren (Dyrenium), Amilorida (Midamor), Asetazolamida (Diamox), Metalazon (Zaroxolyn)
Diuretik
bekerja pada bagian tubulus ginjal yang berbeda untuk menghambat reabsorpsi
natrium dan air dan meningkatkan eksresinya. Kecuali diuretik hemat
-kalium-spironolakton , triamteren, dan amilorida. Diuretik juga meningkatkan
eksresi kalium, meningkatkan risiko hipokalemia. Tujuan dari pemberian diuretic
adalah untuk mencapai status euvolemia dengan dosis yang serendah mungkin,
yaitu harus diatur sesuai kebutuhan pasien, untuk menghindari dehidrasi atau
resistensi.
Cara
pemberian diuretik pada pasien gagal jantung:
1) Pada saat pemberian diuretik periksa fungsi ginjal dan
serum elektrolit
2) Dianjurkan untuk memberikan diuretic pada saat perut
kosong
3) Sebagian besar pasien mendapat terapi diuretik loop
dibandingkan tiazid karena efisiensi diuresis dan natriueuresis lebih tinggi
pada diuretic loop. Kombinasi keduanya dapat diberikan untuk mengatasi keadaan
edema yang resisten
4) Mulai dengan dosis yang kecil dan tingkatkan sampai
perbaikan gejala dan tanda kongesti
5) Pada pasien rawat jalan, edukasi diberikan agar pasien
dapat mengatur dosis diuretic sesuai kebutuhan berdasarkan berat badan harian
dan tanda-tanda klinis dari retensi cairan
d)
Agen Intropik
Positif
1)
Digitalis
Glikosida: Digoksin (Lanoxin), Digoksin (Lanoxin)
Digitalis
memperbaiki kontraktilias miokardium dengan mengganggu ATP-ase dalam membran
sel miokardium dan meningkatkan jumlah kalsium yang tersedia untuk kontraksi.
Peningkatan tenaga kontraksi menyebabkan pengosongan jantung lebih komplet,
meningkatkan volume sekuncup dan curah jantung. Perbaikan curah jantung
memperbaiki perfusi ginjal, menurunkan sekresi renin. Ini menurunkan preload
dan afterload, mengurangi beban jantung. Digitalis juga mempunyai efek
elektrofisiologis, memperlambat konduksi yang melewati nodus AV. Ini menurunkan
frekuensi jantung dan mengurangi konsumsi oksigen.
Indikasi
pemberian digoksin:
Fibrilasi
atrial:
-
Dengan irama
ventricular saat istirahat >80 x/menit atau saat aktivitas >110-120
x/menit
Irama
sinus:
-
Fraksi ejeksi
ventrikel kiri ≤ 40%
-
Gejala ringan
sampai berat (kelas fungsional II-IV NYHA)
-
Dosis optimal
ACEI dan/atau ARB, penyekat beta dan antagonis aldosterone jika ada indikasi
Kontraindikasi
pemberian digoksin:
-
Blok AV derajat
2 dan 3 (tanpa pacu jantung tetap, hati-hati jika paien diduga sindrom sinus
sakit)
-
Sindrom
pre-eksitasi
-
Riwayat
intoleransi digoksin
2)
Agen
simpatomimetik: Dopamin ( Inotropin), Dobutamin (Dobutrex)
Agen simpatomimetik
menstimulasi jantung, memperbaiki tenaga kontraksi. Dobutamin lebih dipilih
dalam penanganan gagal jantung karena tidak meningkatkan frekuensi jantung
sebanyak dopamin dan mempunyai efek vasolidatorik ringan. Obat-obatan ini
diberikan secara infus intravena dan dapat dititrasi untuk mendapatkan efek
optimal.
3)
Inhibitor
fosfodiesterase: Inamrinon (Inocor), Milrinon (Primacor)
Inhibitor
fosfodiesterase digunakan dalam menangani gagal jantung akut untuk meningkatkan
kontraktilitas miokardium dan menyebabkan vasodilatasi. Efek bersih obat ini adalah
meningkatkan curah jantung dan menurunkan afterload
e)
Calcium Channel
Blockers
Generasi pertama kalsium chanel bloker, seperti
verapamil (Calan), nifedipine (Procardia), dan diltiazem (Cardizem), merupakan
kontraindikasi pada pasien dengan gagal
jantung sistolik, walaupun dapat digunakan pada
pasien dengan gagal jantung diastolik.
Amlodipin (Norvasc) dan felodipine (Plendil), yang merupakan penghambat saluran
kalsium dihydropyridine, menyebabkan vasodilatasi, mengurangi resistensi
vaskular sistemik. Obat tersebut dapat
digunakan untuk memperbaiki gejala, terutama pada pasien dengan kardiomiopati
non-epidemi.
f) Hydralazine dan Isosorbide Dinitrate (H-ISDN)
Pada pasien gagal jantung dengan fraksi ejeksi
ventrikel ≤ 40%, kombinasi H-ISDN digunakan sebagai alternative jika pasien
intoleran terhadap ACEI dan ARB.
Indikasi pemberian kombinasi H-ISDN:
1)
Pengganti ACEI
dan ARB dimana keduanya tidak dapat ditoleransi
2)
Sebagai terapi
tambahan ACEI jika ARB atau antagonis aldosterone tidak dapat ditoleransi
3)
Jika gejala
pasien menetap walaupun sudah diterapi dengan ACEI, penyekat beta dan ARB atau
antagonis aldosteteron
Kontraindikasi pemberian kombinasi H-ISDN:
1)
Hipotensi
simtomatik
2)
Sindroma lupus
3)
Gagal ginjal
berat
Inisiasi pemberian kombinasi
H-ISDN:
1)
Dosis awal :
hydralazine 12,5 mg dan ISDN 10mg, 2-3 x/hari
2)
Pertimbangkan
menaikkan dosis secara titrasi setelah 2-4 minggu
3)
Jangan naikkan
dosis jika terjadi hipotensi simtomatik
Efek tidak menguntungkan
yang dapat timbul akibat pemberian kombinasi H-ISDN:
1)
Hipotensi
simtomatik
2)
Nyeri sendi atau
nyeri otot
2.
Nutrisi dan
Aktivitas
Diet terbatas natrium dianjurkan untuk meminimalkan
retensi natrium dan air. Asupan biasanya dibatasi hingga 1,5 sampai 2 gram
natrium perhari,
Intoleransi latihan fisik, penurunan kemampuan untuk
ikut dalam aktivitas yang memakai otot rangka besar akibat keletihan atau
dispnea, adalah manifestasi awal yang umum pada gagal jantung. Aktivitas
mungkin dibatasi hingga tirah baring selama episode akut gagal jantung untuk
menurunkan beban kerja jantung. Namun tirah baring lama dan pembatasan
aktivitas terus-menerus tidak dianjurkan. Program aktivitas sedang yang
progresif dianjurkan untuk memperbaiki fungsi miokardium. Latihan fisik harus
dilakukan 3 sampai 5 hari per minggu dan tiap sesi harus terdiri atas 10 sampai
15 menit periode pemanasan, 20 sampai 30 menit latihan pada intensitas yang
dianjurkan, dan periode pendinginan (LeMone et al., 2015).
3.
Terapi Tambahan
dan intervensi lain
Terapi
oksigen mungkin diperlukan saat gagal
jantung berlangsung. Kebutuhan didasarkan pada tingkat
keparahan kongesti
paru dan hipoksia yang dihasilkan. Beberapa pasien hanya membutuhkan oksigen
tambahan selama periode aktivitas
Pada gagal jantung stadium akhir, alat untuk
menyediakan bantuan sirkulasi atau pembedahan dapat dibutuhkan. Pembedahan
dapat digunakan untuk menangani penyebab dasar kegagalan ( mis. Penggantian
katup yang rusak) atau memperbaiki mutu hidup. Transplantasi jantung saat ini
adalah penangan bedah satu-satunya yang terbukti efektif untuk gagal jantung
stadium akhir (LeMone et al., 2015).
10. Pencegahan Gagal
Jantung
Gagal jantung
merupakan salah satu penyakit kardiovaskuler. Sebagian besar penyakit kardiovaskular dapat dicegah
dengan mengatasi faktor-faktor risiko perilaku seperti penggunaan tembakau,
pola makan dan obesitas yang tidak sehat, aktivitas fisik yang kurang, dan
penggunaan alkohol yang berbahaya. Penyakit kardiovaskular atau yang berisiko kardiovaskular tinggi (karena
adanya satu atau lebih faktor risiko seperti hipertensi, diabetes,
hiperlipidemia atau yang sudah gagal jantung ) perlu deteksi dini dan manajemen konseling dan obat-obatan yang tepat (WHO, 2017).
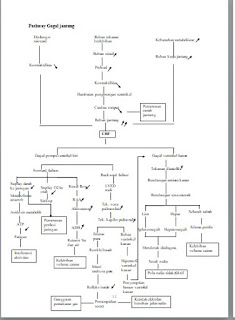
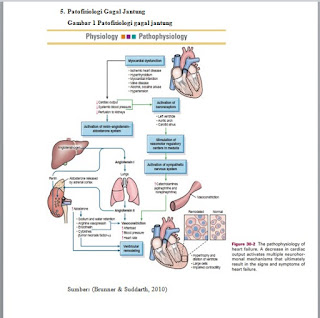

Komentar
Posting Komentar